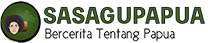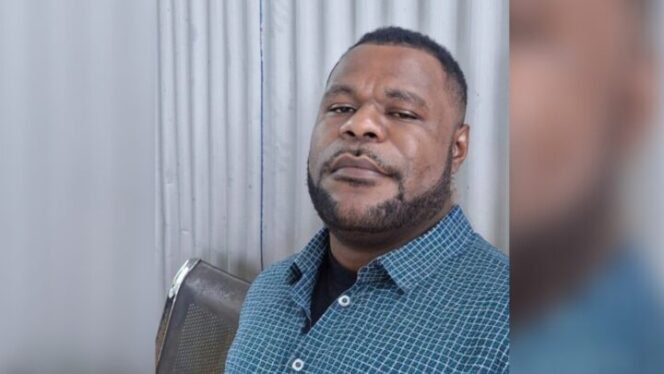Oleh Dekthon Noris Mote
Pemekaran daerah dalam bentuk DOB selalu diproyeksikan sebagai solusi mendekatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan desentralisasi sebagai instrumen anti-sentralisasi.
UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua memberikan mandat khusus melalui Pasal 76: pemekaran provinsi dan kabupaten/kota di Papua dapat dilakukan tanpa tahapan daerah persiapan.
UU No. 15 Tahun 2022 menetapkan Kabupaten Mimika sebagai bagian Provinsi Papua Tengah. Aspirasi pemekaran Mimika Barat dan Mimika Timur dibingkai sebagai upaya mengakhiri ketimpangan pembangunan yang bertumpu di Timika. Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa menargetkan komposisi 80% ASN OAP untuk mempercepat representasi masyarakat Papua dalam birokrasi pemerintahan.
Seminar studi kelayakan DOB Mimika Timur pada 27 September 2024 menegaskan pentingnya menguji faktor fundamental: ekonomi, sosial budaya, pendidikan, kesehatan, politik, jumlah penduduk, hingga kualitas SDM. Namun muncul peringatan penting: pengalaman banyak DOB di Indonesia menunjukkan penurunan layanan publik pada tahap awal.
Paradoks ini mengindikasikan percepatan administratif tidak berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.
Landasan hukum “jalur cepat” pemekaran wilayah tidak disertai mekanisme perlindungan memadai bagi masyarakat adat.
SK Bupati Mimika Nomor 110 dan 113 Tahun 2012, diterbitkan oleh Klemen Tinal dan direvisi 2016 oleh Eltinus Omaleng, menunjukkan proses perencanaan pemekaran telah berlangsung lebih dari satu dekade.
Tidak ada transparansi jelas terkait keterlibatan masyarakat adat pemilik ulayat dalam penyusunan dan pengambilan keputusan regulasi pemekaran, sehingga partisipasi mereka sulit dipastikan.
Harapan terbesar DOB berasal dari masyarakat adat Amungme dan Kamoro yang menuntut agar sejarah marginalisasi tidak terulang. Ketika Kabupaten Mimika dimekarkan dari Kabupaten Fakfak (1996), mereka menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Sumber daya alam dikuras, tambang emas dan tembaga Freeport jadi komoditas global, sementara masyarakat asli tetap hidup dalam kemiskinan struktural.
Representasi birokrasi Kabupaten Mimika menunjukkan proporsi ASN dari Amungme dan Kamoro masih sangat kecil. Pertanyaan kritis: apakah DOB benar-benar solusi struktural mengatasi marginalisasi historis, atau sekadar memperbanyak struktur administratif tanpa mengubah ketimpangan?
Implementasi UU Otsus Tanpa Safeguard
UU No. 2 Tahun 2021 Pasal 76 memberikan kewenangan khusus mempercepat pemekaran di Papua tanpa tahapan daerah persiapan. Pasal ini dirancang mengatasi hambatan birokratis yang memperlambat proses pemekaran di Papua.
Percepatan ini menjadi bumerang ketika tidak disertai mekanisme perlindungan bagi masyarakat adat. Kasus pemekaran Mimika Barat dan Mimika Timur menunjukkan “jalur cepat” dalam Otsus memintas tahapan konsultasi publik yang melibatkan masyarakat adat secara substantif.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa mengusulkan pemekaran beberapa kabupaten termasuk Mimika pada 2025 dengan penekanan percepatan administratif ketimbang perlindungan hak-hak adat.
Problem struktural muncul ketika target 80% ASN OAP tidak secara spesifik mengamanatkan prioritas bagi masyarakat adat pemilik ulayat seperti Amungme dan Kamoro maupun daerah lainnya yang juga merupakan target DOB.
Tanpa spesifikasi ini, target tersebut berpotensi kontraproduktif: memang OAP mengisi posisi ASN di DOB, tetapi bukan OAP pemilik tanah ulayat.
Implementasi Pasal 76 tanpa klausul perlindungan khusus bagi masyarakat adat pemilik ulayat menciptakan celah hukum berbahaya. DOB yang terbentuk melalui jalur cepat berpotensi menciptakan marginalisasi berlapis: masyarakat adat tidak hanya terpinggirkan oleh Non-OAP, tetapi juga oleh OAP dari wilayah lain yang memiliki modal pendidikan, jaringan politik, dan pengalaman birokrasi lebih kuat. Kondisi ini bertentangan dengan semangat Pasal 76 ayat (4) UU No. 2 Tahun 2021 yang menegaskan “pemekaran daerah harus memastikan ruang partisipasi OAP dalam politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial-budaya.”
Kelemahan safeguard dalam implementasi Pasal 76 terlihat dari tidak adanya mekanisme konsultasi wajib dengan lembaga adat sebelum pemekaran dilakukan. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Tanpa konsultasi memadai, pemekaran berisiko melanggar hak-hak konstitusional masyarakat adat. Pemekaran di Papua Tengah menunjukkan bahwa tanpa safeguard, DOB justru memperpanjang marginalisasi.
Kesenjangan UU Otsus
UU No. 2 Tahun 2021 memberikan mandat tegas mengenai kebijakan afirmasi bagi OAP yang seharusnya menjadi landasan mengatasi marginalisasi historis.
Pasal 56 ayat (6) menekankan kewajiban pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan hingga jenjang pendidikan tinggi khusus bagi OAP.
Pasal ini bukan sekadar kewajiban moral, melainkan imperatif hukum yang harus diterjemahkan dalam alokasi APBN dan APBD. Realitas di lapangan menunjukkan alokasi anggaran khusus belum terealisasi secara optimal, terutama dalam bentuk beasiswa afirmatif yang menjangkau seluruh wilayah Papua termasuk Mimika.
Pasal 38 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021 menegaskan bahwa kegiatan perekonomian di Papua wajib mengutamakan tenaga kerja Orang Asli Papua (OAP), namun dalam praktik di Kabupaten Mimika, prinsip ini jauh dari terealisasi.
Masyarakat Amungme-Kamoro tetap menjadi penonton dalam eksploitasi sumber daya alam dan pengelolaan layanan publik di tanah leluhur mereka, sementara perusahaan tambang seperti Freeport serta berbagai BUMN seperti Bank BRI, Sucofindo, Bank Mandiri, PT Pos, PT Pegadaian, Telkom, Telkomsel, Pertamina, Perum Bulog, PT Pelni, PT PLN, Bank BNI, Airnav, dan PT Garuda Indonesia tidak menerapkan prioritas rekrutmen bagi masyarakat asli.
Pasal 6 dan 6A UU No. 2 Tahun 2021 menjamin keterwakilan OAP dalam DPRP dan DPRK, sedangkan Pasal 76 ayat (4) mensyaratkan pemekaran daerah harus memastikan ruang partisipasi OAP dalam politik, pemerintahan, ekonomi, dan sosial-budaya. Mandat yang sudah jelas ini hingga kini belum diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan.
Representasi politik OAP, khususnya masyarakat adat pemilik ulayat, sudah ada pada lembaga legislatif di Mimika maupun Provinsi namun menduduki jabatan tanpa ada pergerakan yang dapat memengaruhi masyarakat secara menyeluruh.
PP No. 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua, khususnya Pasal 4–6, memberi kewenangan operasional bagi daerah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi Orang Asli Papua (OAP), sementara PP No. 107 Tahun 2021, terutama Pasal 2–3 dan Pasal 21 tentang rencana induk percepatan pembangunan Papua, menjadi dasar penting untuk memastikan keberpihakan negara terhadap OAP; meskipun perangkat hukum pusat tersedia, hingga kini belum ada regulasi daerah yang bersifat mengikat, dan Pasal 20 UU No. 2 Tahun 2021 menegaskan peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam memberi pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan DPRP bersama gubernur, seharusnya menjadi instrumen lex specialis untuk menjamin perlindungan hak OAP secara mengikat; tanpa Perdasus, seluruh mandat afirmasi dalam UU maupun PP hanya menjadi janji normatif tanpa daya paksa.
Transparansi Studi Kelayakan
Studi kelayakan pemekaran Mimika yang melibatkan Universitas Papua (UNIPA) berlangsung dalam rentang panjang sejak 2021.
Rangkaian seminar memperlihatkan lemahnya transparansi dan rapuhnya integritas akademik. UNIPA melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menggelar seminar terkait DOB pada 2021 dan awal 2022, tetapi hasil kajian tidak pernah dipublikasikan.
Tidak ada laporan riset, policy brief, atau dokumen resmi yang dapat diuji secara publik. Ketiadaan publikasi ini menciptakan defisit demokratis dalam proses pengambilan keputusan.
Masyarakat tidak diberi kesempatan menilai metodologi, melihat data lapangan, atau menguji argumentasi yang dipakai untuk menilai kelayakan pemekaran. Pemerintah yang mengetahui studi kelayakan kemudian meminta dukungan masyarakat tanpa transparansi.
Akademisi yang semestinya mendorong keterbukaan justru memilih diam, membiarkan hasil riset terkunci di ruang birokrasi.
Situasi berulang pada rangkaian seminar 2024-2025. Forum-forum ini lebih menekankan optimisme birokrasi ketimbang evaluasi akademis yang kritis. Peringatan penting bahwa banyak DOB di Indonesia mengalami penurunan layanan publik pada tahap awal justru tenggelam di balik narasi percepatan administratif.
Si Muda Yang Diam
Paradoks partisipasi pemuda dalam proses DOB Mimika menunjukkan kontradiksi mengkhawatirkan. Generasi muda Amungme-Kamoro memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan generasi sebelumnya berkat investasi LPMAK/YPMAK yang telah menghasilkan ratusan bahkan ribuan sarjana.
Keterlibatan mereka dalam diskusi formal maupun informal tentang DOB masih sangat minim. Keputusan DOB akan berdampak langsung pada masa depan anak-cucu mereka.
Fenomena “silent generation” ini menciptakan legitimacy gap yang fundamental. Ketika keputusan DOB lahir dari konsensus yang tidak melibatkan secara proporsional elemen masyarakat terbesar dan terdidik, maka legitimasi sosial kebijakan tersebut menjadi rapuh. Potensi strategis pemuda sebagai change agents justru terabaikan dalam dinamika ini.
Solusi transformatif memerlukan perubahan paradigma dari “konsultasi tokenistik” menjadi “co-governance participatory”.
Pemuda harus diberi ruang untuk membentuk Youth Advisory Council yang memiliki mandat formal dalam proses DOB, bukan sekadar diundang sebagai pendengar dalam seminar-seminar uji kelayakan.
Council ini dapat mengembangkan riset tandingan, melakukan public hearing di kampung-kampung, dan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mencerminkan aspirasi generasi muda. Momentum kritis untuk mengaktivasi partisipasi pemuda adalah melalui Deklarasi Besar Kedua Suku yang diinisiasi dan dipimpin oleh generasi muda.
Fragmentasi Kelembagaan Adat
Fragmentasi kelembagaan adat menjadi masalah internal serius bagi masyarakat Amungme dan Kamoro.
Lembaga Musyawarah Adat Amungme (LEMASA) dan Lembaga Musyawarah Adat Kamoro (LEMASKO) mengalami dualisme bahkan tigaisme dalam kepengurusan. Terdapat beberapa kelompok kepengurusan yang bersaing dalam satu lembaga, sehingga menimbulkan kebingungan di tingkat masyarakat karena tidak ada satu lembaga adat yang secara jelas diakui sebagai representasi sah. Upaya penyelesaian telah dilakukan oleh Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Tengah dan Badan Kesbangpol Kabupaten Mimika, namun hasilnya belum optimal.
Kondisi ini melemahkan posisi tawar masyarakat adat dan menimbulkan kesulitan dalam membangun legitimasi sosial serta kepastian hukum untuk setiap keputusan adat.
Meski demikian, dinamika ini mulai menemukan arah penyelesaiannya melalui Musyawarah Adat (Musdat) Suku Amungme pada 30 Agustus 2025 yang menghasilkan Deklarasi Amungun. Deklarasi ini meneguhkan Lemasa versi Musdat sebagai lembaga adat sah milik seluruh masyarakat hukum adat Amungme yang terbentuk dari konfederasi 13 wilayah pemerintahan adat dan 1 wilayah diaspora. Lemasa ditegaskan bukan milik marga tertentu atau perorangan, melainkan kolektif seluruh orang Amungme.
Forum Musdat juga menegaskan kembali jasa pendiri Lemasa, almarhum Tom Beanal, yang merintis lembaga ini sebagai forum suci perjuangan adat. Dengan demikian, Musdat 2025 menjadi forum tertinggi yang mengikat secara adat, moral, dan hukum untuk menutup ruang fragmentasi serta mempertegas legitimasi kelembagaan adat.
Pembelajaran dari Pengalaman Mimika
1. Paradoks Investasi Pendidikan vs Akses Kerja
Pembentukan Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK) pada 2002 dan transformasinya menjadi Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pada 2019 merupakan salah satu capaian penting dalam perjalanan Mimika.
Program beasiswa yang dikelola lembaga ini berhasil melahirkan ratusan hingga ribuan sarjana, magister dari masyarakat Amungme, Kamoro, dan lima suku kerabat lainnya. Dari sisi peningkatan kualitas pendidikan, pencapaian ini patut diapresiasi karena berhasil memperkecil kesenjangan pendidikan yang selama puluhan tahun dialami masyarakat adat.
Namun, paradoks besar muncul ketika pencapaian pendidikan tidak dibarengi dengan jaminan akses lapangan kerja. YPMAK periode 2002–2024 tercatat lebih dari seribu penerima beasiswa berhasil menyelesaikan pendidikan tinggi di dalam dan luar negeri.
Tetapi, hanya sekitar 30-40% yang terserap di birokrasi daerah atau perusahaan tambang sedangkan yang lainya menjadi pengangguran terdidik tanpa akses ke lapangan kerja.
Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi pendidikan tinggi belum menghasilkan transformasi ekonomi dan sosial yang signifikan. Padahal, Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2021 menegaskan kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, mengalokasikan anggaran hingga jenjang pendidikan tinggi bagi OAP, menyediakan sarana prasarana, serta menjamin kesejahteraan tenaga pendidik. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan bagi OAP bukan sekadar pemberian beasiswa, tetapi merupakan afirmasi yang harus diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia Papua yang berdaya saing.
Dengan demikian, pendidikan tidak boleh berhenti pada pencapaian gelar akademik semata, melainkan harus diintegrasikan dengan kebijakan afirmatif lain yang membuka akses bagi OAP menuju kemandirian ekonomi dan keterhubungan dengan pasar kerja.
Lulusan Amungme-Kamoro yang telah mengenyam pendidikan tinggi tetap terpinggirkan dalam rekrutmen CPNS, BUMN, BUMD, maupun perusahaan tambang yang beroperasi di atas tanah adat mereka sendiri. Lebih jauh, akses ke sekolah-sekolah kedinasan (seperti IPDN, PKN STAN, STIN, dll) yang seharusnya menjadi saluran penting bagi regenerasi birokrasi dan kepemimpinan strategis juga belum memiliki jalur afirmatif khusus bagi OAP terkhususnya pemilik hak ulayat. Dengan kata lain, Mimika baik melalui bantuan beasiswa LPMAK/YPMAK maupun pemerintah daerah telah membangun modal manusia tetapi gagal menyiapkan struktur peluang.
Jika situasi ini tidak segera diperbaiki, DOB hanya akan memperbanyak lulusan terdidik yang kembali ke kampung sebagai “penonton” di tanah sendiri.
2. Dampak Lingkungan dan Sustainability
Krisis lingkungan akibat aktivitas pertambangan PT Freeport Indonesia telah berlangsung lebih dari setengah abad di Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Setiap hari, sekitar 300 juta ton limbah tailing dibuang ke sungai dan laut, mencemari ekosistem dari hulu hingga muara serta pesisir, termasuk 23 kampung yang menjadi rumah bagi masyarakat adat Suku Sempan, Kamoro, Amungme, dan suku kecil lainnya.
Sungai yang selama ribuan tahun menjadi sumber transportasi, pangan, dan budaya kini tercemar berat, mengalami pendangkalan, dan kehilangan keanekaragaman hayati.
Data Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menunjukkan bahwa produksi satu gram emas dari tambang Freeport menghasilkan 2,1 ton material sisa dan 5,8 kilogram emisi beracun berupa logam berat seperti arsenik, timbal, merkuri, dan sianida. Limbah ini tidak hanya merusak sungai, tetapi juga hutan, muara, dan wilayah pesisir, dengan kerugian ekosistem yang diperkirakan mencapai Rp 185 triliun (BPK, 2017). Kolam penampungan tailing (ModADA) di bantaran Sungai Ajkwa terbukti meluap, menambah risiko pencemaran di lima sungai lain di Mimika. Dampak ekologis ini berimplikasi langsung pada masyarakat, merusak tanaman tradisional, menghancurkan pohon sagu sebagai sumber pangan, mematikan habitat ikan, serta meningkatkan risiko penyakit bagi anak-anak dan perempuan akibat paparan limbah beracun.
Siaran pers JATAM (Februari 2023) dan laporan media Betahita (April 2023) menegaskan bahwa Freeport dan pemerintah lebih fokus pada keuntungan finansial dan saham daripada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.
Aktivitas ini telah menyebabkan degradasi wilayah pesisir, hilangnya muara Sungai Ajkwa, serta mengancam pulau-pulau seperti Piriri, Bidadari, Kelapa, dan Yapero. Upaya perlawanan warga yang diwakili John Gobay (Ketua Poksus Papua) dan Adolfina Kuum (Yayasan Lepemawi) diajukan ke DPR RI untuk mendesak audit menyeluruh terhadap operasi Freeport. Kepala Divisi Hukum JATAM, M.
Jamil, menegaskan bahwa akuisisi saham pemerintah Indonesia (51,2%) tidak memperkuat kedaulatan negara atau memastikan penegakan hukum terhadap kejahatan korporasi, dan pembiaran praktik ilegal Freeport menunjukkan pelanggaran terang-terangan terhadap konstitusi UUD 1945.
Krisis lingkungan ini juga menjadi faktor krusial dalam perencanaan pemekaran DOB baru di Mimika. Fragmentasi administratif menjadi Mimika Barat, Mimika Timur, dan rencana Kota Madya Timika tanpa koordinasi pengelolaan lingkungan yang terpadu hanya akan memperparah kerusakan ekosistem dan membuka celah bagi perusahaan mengeksploitasi kelemahan regulasi. DOB baru berisiko menghadapi dilema antara kebutuhan pendapatan daerah dari sektor pertambangan dan tuntutan perlindungan lingkungan, sementara masyarakat adat akan kehilangan tanah ulayat, sumber pangan tradisional, dan hubungan kultural dengan ruang hidup mereka.
Pengalaman Mimika menjadi peringatan bahwa pemekaran tanpa kerangka perlindungan lingkungan yang kokoh justru memperdalam ketimpangan, melanggengkan praktik eksploitatif, dan mempercepat krisis ekologis.
3. Risiko Fragmentasi Administratif
Pemecahan Kabupaten Mimika dengan luas sekitar 21.000 km² menjadi tiga entitas administratif membawa konsekuensi serius bagi masyarakat adat. Jika pola marginalisasi tidak dikoreksi, masyarakat Amungme dan Kamoro tidak hanya menjadi minoritas di satu kabupaten, tetapi tersebar dan termarginalisasi di tiga entitas sekaligus. Hal ini membuka celah bagi kelompok Non-OAP dan OAP dari wilayah lain yang memiliki modal di dalam maupun luar birokrasi dan perusahaan untuk cepat mendominasi ruang strategis, sehingga berpotensi menciptakan elite capture lebih parah.
Pengalaman Kabupaten Mimika menunjukkan ketergantungan pada industri tambang tanpa pengawasan ketat memperparah kerusakan ekologis sekaligus menyingkirkan kepentingan masyarakat lokal.
Fragmentasi administratif tidak otomatis memperbaiki tata kelola. Sebaliknya, ia membuka ruang kompetisi antar DOB baru dalam “menjual murah” wilayah kepada perusahaan.
Persaingan ini melemahkan posisi tawar masyarakat adat sekaligus mempermudah perusahaan menguasai ruang hidup dengan memanfaatkan perbedaan regulasi dan kepentingan politik lokal.
Peringatan tentang risiko DOB ini juga pernah disampaikan oleh Gubernur Papua (alm.) Lukas Enembe, yang menegaskan semua pihak harus memikirkan dampak negatif pemekaran yang didorong DPR RI. Menurutnya, hal terpenting adalah proteksi nyata bagi orang asli Papua, sebab perlindungan tersebut belum maksimal.
Ia menekankan DOB harus benar-benar mensejahterakan masyarakat, bukan sekadar menyerap dana infrastruktur. Suara kritis almarhum menjadi pengingat bahwa pemekaran tanpa proteksi kuat hanya akan memperparah marginalisasi masyarakat adat di tanahnya sendiri.
Solusi
1. Kerangka Hukum Afirmatif
Prioritas utama adalah menyusun Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) berbasis UU Otsus Papua yang mengatur secara tegas komposisi rekrutmen CPNS dengan kuota afirmatif: 70–80% untuk Amungme dan Kamoro sebagai pemilik ulayat, 10–20% untuk OAP lainnya, dan maksimal 10% untuk Non-OAP. Perdasus ini harus disinkronkan dengan target Gubernur Meki Nawipa tentang 80% ASN OAP, dengan spesifikasi yang jelas bahwa prioritas utama adalah masyarakat adat pemilik ulayat.
DOB baru harus menandatangani MOU resmi dengan Kemendagri dan BKN agar setiap kali ada rekrutmen CPNS mengacu pada kuota yang berpihak secara jelas.
Mekanisme implementasi harus mencakup: (1) Ujian khusus berbasis konteks lokal dan kearifan adat; (2) Penggunaan bahasa ibu
dalam tes wawancara bila diperlukan; (3) Program pelatihan pra-CPNS atau pra-IPDN bagi calon dari Amungme dan Kamoro yang wajib dilaksanakan; (4) Sistem monitoring dan evaluasi yang transparan dengan publikasi berkala. Penerapan Perdasus ini juga berfungsi sebagai alat pemberdayaan masyarakat adat secara sistematis.
Dengan kuota khusus dan mekanisme seleksi yang adil, generasi muda Amungme dan Kamoro akan memiliki peluang nyata untuk terlibat dalam pemerintahan, memperkuat representasi mereka di lembaga negara, dan mendorong pembangunan yang selaras dengan aspirasi lokal.
Perdasus ini dirancang agar manfaatnya dapat dinikmati lintas generasi. Dengan menempatkan masyarakat adat pemilik ulayat sebagai prioritas dalam berbagai rekrutmen baik BUMN, BUMD, Sekolah Kedinasan, ASN dan membangun fondasi kapasitas generasi muda sejak sekarang, setiap generasi berikutnya akan tetap memiliki akses dan peluang yang adil untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan strategis di wilayah mereka.
2. Renegoisasi Kontrak Perusahaan Tambang
DOB baru harus memanfaatkan kontrak karya atau IUPK sebagai leverage negosiasi. Perusahaan tambang tidak boleh memperpanjang izin atau membuka area baru jika tidak memenuhi syarat afirmasi perekrutan dengan komposisi yang sama: 70–80% Amungme-Kamoro, 10–20% OAP lainnya, dan maksimal 10% Non-OAP. Perusahaan wajib menerapkan perlindungan lingkungan yang transparan dengan sistem monitoring publik.
Addendum kontrak harus berbasis hukum, bukan sekadar program CSR, sehingga kepastian hak masyarakat adat terlindungi secara legal. Perusahaan wajib mengalokasikan formasi kerja langsung untuk masyarakat adat di level teknis, manajerial, dan administratif.
DOB dapat menyiapkan lembaga pelatihan khusus yang mempersiapkan SDM lokal agar memenuhi standar kompetensi perusahaan.
Strategi ini menciptakan sinergi antara pengembangan ekonomi lokal dan perlindungan hak-hak adat. Perusahaan tambang tetap beroperasi secara produktif, sementara masyarakat adat memperoleh akses yang adil terhadap pekerjaan, penghasilan, dan peluang partisipasi dalam pembangunan wilayahnya sendiri.
Renegoisasi kontrak berdasarkan Pasal 38 ayat (3) UU No. 2 Tahun 2021 yang mengatur kegiatan perekonomian di Papua wajib mengutamakan tenaga kerja OAP.
3. Penguatan Mekanisme Kontrol Adat
Penguatan mekanisme kontrol adat dalam implementasi DOB tidak hanya membutuhkan dasar hukum yang kuat, tetapi juga langkah konkret berupa pemetaan wilayah adat dan kajian strategis sosial-budaya.
Proses ini harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pemerhati, akademisi, dan NGO agar menghasilkan data faktual serta analisis mendalam tentang dinamika masyarakat. Dengan demikian, keberadaan lembaga adat tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga berlandaskan pemahaman sosial-budaya yang komprehensif, sehingga setiap keputusan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat adat maupun negara.
Lembaga adat sebagai mekanisme kontrol dalam implementasi DOB harus dipayungi dengan legitimasi hukum yang jelas. Landasan konstitusionalnya sudah tersedia: Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya.
Pasal 67 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan bahwa masyarakat hukum adat berhak mengatur dan mengurus kepentingannya berdasarkan hak asal-usul, menetapkan dan mengelola kelembagaan adat, serta mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
Dalam konteks DOB, kelembagaan adat ini dapat dipayungi melalui Perdasus yang berfungsi sebagai lex specialis.
Melalui Perdasus, monitoring adat tidak lagi bersifat moral atau seremonial, melainkan memiliki kekuatan hukum mengikat untuk mengawasi implementasi kuota afirmatif dalam: penerimaan CPNS, rekrutmen tenaga kerja di BUMN (Telkom, BPJS, PLN, Perbankan, dan lain-lain) maupun BUMD, kontrak kerja dan kemitraan dengan perusahaan tambang, jalur khusus penerimaan sekolah kedinasan seperti IPDN, PKN STAN, STIN, serta peluang kerja di NGO atau lembaga strategis lainnya. Fragmentasi kelembagaan adat LEMASA dan LEMASKO harus diselesaikan melalui Musyawarah Besar Adat yang difasilitasi MRP Provinsi Papua Tengah.
Satu lembaga adat yang legitimate dan diakui secara hukum akan memperkuat posisi tawar masyarakat adat dalam mengawasi implementasi DOB, sekaligus memiliki mandat formal untuk memberikan persetujuan atau penolakan terhadap kebijakan strategis yang berdampak pada tanah ulayat dan hak-hak adat.
Penguatan kelembagaan adat juga harus memastikan adanya kontribusi suara perempuan dalam struktur maupun pengambilan keputusan. Hal ini sejalan dengan Pasal 5 ayat (2) UU Otsus yang menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu mandat utama MRP, serta Pasal 20 dan Pasal 6A yang mewajibkan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% di DPRP dan DPRK.
Kehadiran perempuan Amungme-Kamoro bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian integral dari representasi adat yang sejati. Dengan melibatkan perempuan, suara adat menjadi lebih inklusif, berlandaskan hukum, dan mencerminkan kepentingan seluruh komunitas, bukan hanya para tetua laki-laki.
4. Transparansi Akademik dan Partisipasi Publik
Transformasi peran akademisi menjadi salah satu kunci untuk memastikan proses DOB berjalan transparan dan inklusif.
LP2M UNIPA dan lembaga penelitian lain harus mengubah paradigma kerja mereka, dari sekadar menghasilkan kajian akademik untuk internal menjadi penyedia informasi yang dapat diakses publik secara luas.
Setiap hasil kajian DOB perlu dipublikasikan secara terbuka dalam berbagai format: laporan riset lengkap dengan metodologi yang dapat diverifikasi, policy brief dalam bahasa sederhana untuk masyarakat umum, dokumen populer yang mudah dipahami, siaran radio lokal dalam bahasa daerah, publikasi digital yang dapat diakses melalui media sosial dan website resmi.
Transparansi publik tidak boleh berhenti pada publikasi dokumen. Seminar dan forum akademik yang selama ini bersifat tertutup harus dibuka untuk masyarakat luas. Diskusi publik perlu melibatkan tokoh pemuda dari seluruh Kabupaten Mimika, forum mahasiswa, akademisi, tokoh perempuan, tokoh agama, serta perwakilan masyarakat adat dari setiap kampung.
Metode publikasi yang beragam memiliki peran strategis dalam memperluas jangkauan informasi.
Siaran radio lokal dan media digital memungkinkan masyarakat di daerah terpencil tetap mendapatkan informasi, sementara diskusi di balai adat dan pertemuan langsung membangun interaksi personal yang memperkuat pemahaman dan legitimasi sosial. Keterlibatan publik mendorong akuntabilitas akademisi dan lembaga penelitian.
Lebih jauh, transparansi akademik juga harus dipadukan dengan mekanisme partisipasi publik yang memiliki daya ikat. Artinya, rekomendasi hasil riset dan suara masyarakat dalam forum-forum diskusi tidak hanya berhenti sebagai arsip, tetapi wajib menjadi rujukan formal bagi pemerintah daerah dan DPR dalam setiap proses perumusan kebijakan DOB. Dengan begitu, riset akademik dan partisipasi publik benar-benar memiliki posisi strategis sebagai kontrol sosial, bukan sekadar formalitas partisipasi.
Setiap kajian yang dipublikasikan terbuka dapat diuji kebenarannya oleh masyarakat dan pemangku kepentingan lain. Mekanisme ini meminimalkan risiko bias, kesalahan interpretasi, atau manipulasi data, sekaligus membangun budaya ilmiah yang lebih transparan dan bertanggung jawab.
5. Road Map Pasca Pengesahan
(Berlogikalah) Dalam 100 hari pertama pasca pengesahan DOB, agenda prioritas harus segera dijalankan:
Hari 1-30: Penyusunan draft Perdasus Afirmasi berbasis UU Otsus Papua dengan melibatkan tokoh adat, pemuda, dan akademisi
Hari 31-60: Penandatanganan MOU dengan Kemendagri dan BKN untuk implementasi kuota afirmasi dalam rekrutmen CPNS
Hari 61-90: Renegosiasi kontrak dengan perusahaan tambang untuk klausul afirmasi tenaga kerja dan perlindungan lingkungan
Hari 91-100: Musyawarah Besar Adat untuk menentukan lembaga kontrol
Road map ini disusun sebagai gambaran perencanaan strategis dari berbagai solusi yang telah diuraikan sebelumnya, dan bertujuan memberikan arah serta prioritas langkah-langkah yang dapat diambil pasca pengesahan DOB.
Untuk pelaksanaan teknisnya, seluruh agenda dan kegiatan yang tercantum dapat dijadwalkan, diorganisir, dan direalisasikan oleh tim khusus yang bergerak secara operasional, sehingga setiap solusi dapat diterapkan secara konkret dan berkelanjutan, sambil memastikan manfaatnya dapat dirasakan lintas generasi.
Penutup
DOB tidak boleh berhenti sebagai proyek politik jangka pendek yang hanya memuaskan elit, sementara masyarakat adat tetap terpinggirkan.
Pemekaran wilayah harus menjadi instrumen transformasi struktural yang mengakhiri marginalisasi historis, bukan sekadar perubahan administratif yang memperbanyak birokrasi tanpa substansi. Pertanyaan fundamental yang harus terus diajukan: “DOB untuk berapa generasi?” Apakah manfaatnya hanya 5–10 tahun pertama, atau dirancang memberikan keadilan berkelanjutan bagi generasi perintis hingga mewarisi tanah leluhur?
Indikator keberhasilan DOB Mimika Barat dan Mimika Timur tidak boleh hanya diukur dari gedung pemerintahan atau birokrasi baru.
Indikator harus selaras Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2021, yang menegaskan tiga tujuan utama Otsus: meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat pembangunan, dan melindungi hak dasar OAP. Keberhasilan DOB seharusnya terlihat dari: persentase ASN Amungme-Kamoro di posisi strategis sesuai Pasal 61 ayat (2) UU Otsus; partisipasi masyarakat adat dalam pengambilan keputusan publik, selaras Pasal 18B UUD 1945.
Solusi afirmatif tersedia dan memiliki landasan hukum kuat melalui UU Otsus dan turunannya, khususnya PP No. 106/2021 dan PP No. 107/2021.
Instrumen ini membuka ruang kuota afirmatif lewat Perdasus, pengawasan adat yang terikat hukum, hingga kontrak afirmatif dengan perusahaan tambang. Namun, semua mandat ini akan menjadi wacana kosong jika tidak diterjemahkan ke regulasi daerah yang mengikat. Pengalaman Kabupaten Mimika sejak 1996-2025 menunjukkan bahwa tanpa regulasi tegas, masyarakat Amungme dan Kamoro tetap minoritas di tanah sendiri meski sumber daya dieksploitasi untuk kepentingan global.
Keberadaan DOB Mimika Barat dan Mimika Timur kini menjadi ujian sejarah: apakah pemekaran mampu menjadi instrumen pemulihan kedaulatan Amungme-Kamoro di tanah leluhur, atau justru menjadi fragmentasi administratif yang memperdalam marginalisasi.
Momentum ini menentukan apakah masyarakat adat tetap menjadi penonton di tanahnya sendiri, atau tampil sebagai subjek pembangunan berdaulat sesuai amanat hukum. DOB hanya akan bermakna bila dilandasi regulasi afirmatif yang mengikat, sehingga OAP (terkhusus pemilik tanah ulayat) tidak lagi terpinggirkan di tanahnya sendiri.
Opini ini ditulis oleh Dekthon Noris Mote (penulis adalah cucu tertua dari salah satu mantri perintis dari Suku Mee di Kabupaten Mimika)